Putusan PTUN Menggantung: Keadilan Terhenti di Labirin Birokrasi
- calendar_month Ming, 8 Jun 2025
- visibility 1.388
- comment 1 komentar

Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H.
Seorang praktisi hukum (Advokat) dan akademisi (Dosen)
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk untuk menegakkan keadilan dalam sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, PTUN memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) tidak dieksekusi oleh tergugat, meninggalkan penggugat dalam ketidakpastian hukum. Fenomena ini mencerminkan tantangan sistemik dalam birokrasi yang menghambat keadilan.
Menurut Pasal 79 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan wajib melaksanakan putusan pengadilan yang BHT. Pasal 64 dan 66 UU ini mengatur bahwa pelaksanaan putusan harus dilakukan dalam waktu 21 hari kerja sejak putusan diterima. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1986, khususnya Pasal 116, yang mengatur prosedur eksekusi putusan PTUN. Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa salinan putusan BHT harus dikirimkan kepada para pihak dalam 14 hari kerja oleh panitera pengadilan tingkat pertama.
Jika putusan mengabulkan gugatan, Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 menetapkan kewajiban tergugat untuk: (a) mencabut KTUN yang disengketakan, (b) mencabut KTUN dan menerbitkan yang baru, atau (c) menerbitkan KTUN baru jika sengketa timbul karena ketiadaan keputusan (Pasal 3). Jika tergugat tidak mencabut KTUN dalam 60 hari kerja, keputusan tersebut kehilangan kekuatan hukum (Pasal 116 ayat 2). Untuk kewajiban lain seperti penerbitan KTUN baru, tenggat waktu adalah 90 hari kerja, dan penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi paksa jika kewajiban ini tidak dipenuhi (Pasal 116 ayat 3).
Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 (Juklak 2024) memberikan panduan teknis eksekusi. Angka Romawi II Juklak mengatur pemberitahuan putusan dalam 14 hari kerja, sementara Angka Romawi IV menetapkan eksekusi otomatis setelah 60 hari. Jika tergugat tetap tidak patuh setelah 90 hari, dalam Angka Romawi V memungkinkan eksekusi paksa melalui surat peringatan, penetapan eksekusi, uang paksa, atau sanksi administratif. Pengumuman ketidakpatuhan di media massa juga diwajibkan (Pasal 116 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1986 dan Juklak Angka Romawi V).
Dalam sengketa tertentu, putusan PTUN dapat mencakup ganti rugi atau rehabilitasi. Pasal 97 ayat (10) UU No. 5 Tahun 1986 memungkinkan pembebanan ganti rugi, yang prosedurnya diatur dalam Pasal 120. Salinan putusan ganti rugi harus dikirimkan dalam 3 hari setelah BHT kepada penggugat, tergugat, dan pejabat yang dibebani kewajiban (Pasal 120 ayat 1-2). Juklak 2024 (Angka Romawi VI) menetapkan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ganti rugi dalam 30 hari jika kewajiban tidak dipenuhi. Tata cara pelaksanaan ganti rugi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 (Pasal 120 ayat 3).
Untuk sengketa kepegawaian, Pasal 97 ayat (11) UU No. 5 Tahun 1986 memungkinkan rehabilitasi, yaitu pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat pegawai seperti semula (Pasal 121). Juklak 2024 (Angka Romawi VII) mengatur bahwa rehabilitasi harus mempertimbangkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Jika rehabilitasi tidak memungkinkan karena jabatan telah terisi, Angka Romawi VIII Juklak memungkinkan kompensasi sebagai alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU No. 5 Tahun 1986. Pasal 117 memungkinkan penggugat mengajukan kompensasi dalam 30 hari jika keadaan berubah setelah putusan BHT, dengan ketua pengadilan menetapkan jumlahnya jika tidak ada kesepakatan.
Ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan PP No. 48 Tahun 2016. Sanksi ini mencakup teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian, yang dikenakan oleh atasan pejabat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasal 116 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 juga mengatur uang paksa sebagai upaya paksa, sementara ayat (6) mewajibkan ketua pengadilan melaporkan ketidakpatuhan ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan ke DPR untuk pengawasan.
Juklak 2024 (Angka Romawi V) memperkuat mekanisme ini dengan mengatur pengumuman di media massa dan pemberitahuan ke otoritas terkait. Namun, implementasi sanksi sering terhambat oleh kompleksitas birokrasi, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi atau ketidakjelasan wewenang penegak sanksi.
Meskipun regulasi telah jelas, eksekusi putusan PTUN sering terhambat. Pertama, sikap pejabat yang mengabaikan putusan karena kepentingan pribadi atau institusi sering kali tidak diikuti sanksi tegas. Kedua, kurangnya pengawasan internal oleh atasan pejabat atau APIP memperlambat penegakan sanksi. Ketiga, sengketa kepegawaian yang melibatkan rehabilitasi sering terhenti karena jabatan yang dimaksud telah terisi, memaksa penggugat menerima kompensasi yang tidak selalu memadai.
Angka Romawi X Juklak 2024 mengatur penetapan non-eksekutabel jika putusan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, seperti perubahan hukum atau keadaan force majeure. Namun, penetapan ini terkadang disalahgunakan untuk menghindari eksekusi, merugikan penggugat yang telah memenangkan perkara.
Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, memperkuat pengawasan oleh KemenPAN-RB dan APIP untuk memastikan sanksi administratif PP No. 48 Tahun 2016 ditegakkan secara konsisten. Kedua, memanfaatkan teknologi, seperti domisili elektronik untuk pemberitahuan putusan (Juklak 2024, Angka Romawi II), guna mempercepat proses. Ketiga, membentuk satuan tugas eksekusi putusan PTUN di bawah Mahkamah Agung untuk memastikan koordinasi antarinstansi.
Keempat, meningkatkan kesadaran hukum pejabat melalui pelatihan tentang kewajiban UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1986. Terakhir, DPR perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan (Pasal 116 ayat 6) untuk menekan pejabat yang tidak patuh. Dalam jangka panjang, revisi PP No. 43 Tahun 1991 dapat dilakukan untuk memperbarui mekanisme ganti rugi agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini.
Putusan PTUN yang tidak dieksekusi mencerminkan kegagalan birokrasi dalam menegakkan keadilan. UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 48 Tahun 2016, UU No. 5 Tahun 1986, dan Juklak 2024 telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, namun implementasinya terhambat oleh sikap pejabat, kurangnya pengawasan, dan kompleksitas prosedur. Dengan penguatan sanksi, teknologi, dan koordinasi antarinstansi, PTUN dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan, memastikan bahwa putusan tidak hanya menjadi kertas di labirin birokrasi, tetapi benar-benar mengembalikan hak warga negara.
- Penulis: Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H.
- Editor: Tatandak.id





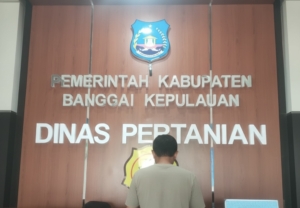













Jika terjadinya pelanggaran birokrasi yang mengulur waktu untuk pembayaran ganti rugi tanaman warga negara indonesia. Apakah masuk dalam tidak pidana?
19 Januari 2026 9:39 pm